Satu Tempat Beribu Makna: Tugu Yogyakarta sebagai Perwujudan Memori Kolektif Masyarakat & Wisatawan
- reza altamaha

- Jun 28, 2019
- 29 min read
Oleh: Hanna Rahmayani Wisnuputri
Terdapat berbagai macam cara untuk melihat sebuah kota. Kawasan perkotaan sebagai pusat berbagai aktivitas masyarakat telah membentuk konstruk citra sebuah kota. Terciptanya citra sebuah kota yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini dapat diwujudkan secara fisik maupun sosial. Wujud dan sifat dari citra sebuah kota yang secara empiris dapat dirasakan secara bersamaan telah membentuk memori atau pemahaman orang luar untuk mengenali sebuah kota. Dibentuknya sebuah ikon atau landmark kota dalam hal ini memiliki peranan penting dalam menciptakan citra dan pemahaman akan sebuah kota. Mengambil kasus Tugu Yogyakarta yang dikenal sebagai sebuah penanda bagi wisatawan untuk mengambil foto di monumen ini sebagai bukti kunjungan ke Yogyakarta. Adanya berbagai pemaknaan terhadap monument ini dikalangan masyarakat dan wisatawan turut menyumbang terbentuknya konstruksi baru mengenai citra Yogyakarta. Untuk melihat implikasi dari perbedaan pemaknaan tersebut akan dimulai dengan memahami secara historis dan kontemporer mengenai Tugu Yogyakarta.
Daya Tarik Tugu Yogyakarta
Kawasan Tugu Yogyakarta merupakan Central Bussiness District (CBD) selain Malioboro, bedanya jika Malioboro dikenal sebagai tempat belanja murah meriah, kawasan Tugu Yogyakarta dipenuhi oleh hotel-hotel berbintang pencakar langit. Sebut saja Hotel Harper, Hotel Arjuna, Grand Zuri Malioboro Hotel, The 101 Yogyakarta Tugu Hotel, Horison Ultima Riss Hotel Malioboro, Pop Hotel, dan lain-lain. Selain itu, juga terdapat cafe-cafe estetik untuk ‘nongkrong’ yang instagramable seperti Roaster and Bear, Madam Tan Resto, Honje Resto tentunya dengan budget yang fantastis pula. Adapula tempat nongkrong murah meriah yang tidak kalah pamornya dari cafe highclass dan juga digemari oleh anak muda, sebut saja Angkringan KR dan Umah Kopi Gayo di Jalan Mangkubuni, Warmindo Andeska dan Kampoeng Tugu Foodcourt di Jalan AM Sangaji, dan Angkringan Mas Bagong yang terletak di Jalan Jendral Soedirman tidak mengurangi kenikmatan suasana Tugu Yogyakarta diwaktu malam.
Saat pagi hari, disaat aktivitas lalu lintas belum seramai pukul 10:00 pagi, dapat ditemukan beberapa pejalan kaki maupun pengguna sepeda yang sekedar berolahraga pagi maupun istirahat sebentar di pelataran Diorama Tugu Golong Gilig yang diresmikan Oktober 2015. Menariknya dari diorama ini masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Tugu Yogyakarta dapat mengetahui sejarah Tugu Yogyakarta yang telah berumur hampir 3 abad lamanya. Selain terdapat diorama, disepanjang pedestrian Jalan Mangkubumi juga terdapat stasiun sepeda yang dapat dipinjam oleh masyarakat lokal maupun wisatawan. Stasiun sepeda juga dapat ditemui shelter Suroto, Taman Pintar, Terang Bulan, Benteng Vredeburg, Kepatihan, Mall Marlioboro, Loko Cafe, Gondolayu, Tugu, Hotel Harper, Kedaulatan Rakyat dan Hotel Grand Zury (data shelter sepeda dari aplikasi inabike) semuanya merupakan kerja sama dari Pertamina, Mandiri, PT. WIKA dan lain-lain menunjukkan pengembangan wisata sekitar Tugu Yogyakarta sangat didukung oleh perusahaan besar di Indonesia. Cara untuk menyewa sepeda ini sangat mudah, penyewa hanya meng-install aplikasi inabike di smartphone masing-masing, konfirmasi dan memindai QR code yang tersedia di sepeda.
Tugu Yogyakarta sebagai infrastruktur yang telah dibangun sangat lama dapat menjadi saksi peristiwa yang telah terjadi dari masa lampau hingga kini. Selain menjadi di landmark Yogyakarta, tujuan wisata swafoto, dan wisata sejarah, Tugu Yogyakarta juga pernah dijadikan sebagai ruang demokrasi, seperti ditahun lalu terdapat aksi Solidaritas Antar Agama karena adanya aksi terorisme di Surabaya lalu ada pula aksi yang berkaitan dengan menuju pemilihan presiden 2019. Di masa lampau, saat Tugu Yogyakarta masih berbentuk Tugu Golong Gilig, disimbolkan sebagai persatuan rakyat dan penguasa dalam melawan kolonialisasi. Andai Tugu Yogyakarta bisa berbicara, mungkin ia akan menceritakan pengalamannya dalam menyaksikan peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta.
Sejarah Tugu Yogyakarta
Tugu saat ini dibangun oleh pemerintah Belanda setelah tugu sebelumnya runtuh akibat gempa yang terjadi waktu itu. Tugu sebelumnya yang bernama Tugu Golong-Gilig dibangun oleh Hamengkubuwana I pada tahun 1756, pendiri kraton Yogyakarta pasca pemisahan Kerajaan Mataram Islam menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasultanan Surakarta. Pembangunan tugu ini dilakukan untuk memperingati persatuan antara raja (pada saat itu Pangeran Mangkubumi) dengan rakyat dalam melawan Kolonial Belanda (pamungkaz.net). Tidak hanya itu saja, konon Sultan Yogyakarta pada waktu itu menggunakan tugu ini sebagai patokan arah menghadap puncak gunung Merapi (Wikipedia.org).
Perubahan bentuk Tugu Yogyakarta saat ini sudah dimulai saat pembangunan kembali tugu pada tanggal 10 Juni 1867. Terjadinya perubahan bentuk tugu ini diawali dengan adanya peristiwa terpotongnya Tugu Golong-Gilig sepertiga bagian akibat gempa pada tahun EHE 1284 H atau 1796 Tahun Jawa sekitar pukul 05.00 pagi. Pendirian kembali tugu ditangani oleh Opzichter van Waterstaat/Kepala Dinas Pekerjaan Umum, JWS van Brussel, di bawah pengawasan Pepatih Dalem Kanjeng Raden Adipati Danurejo V. Tugu kemudian diresmikan HB VII pada 3 Oktober 1889 atau 7 Sapar 1819 Tahun Jawa. Oleh pemerintah Belanda, tugu itu disebut De Witte Paal (Tugu Putih). Penamaan tersebut didasarkan pada fungsi tugu sebagai paal atau tonggak yang dicat/dikapur putih hingga tampak jelas dari kejauhan (Upacara Tradisional Jumenengan, 1995:116 dalam Morin, 2014:136).

Seperti gambar diatas, Tugu Yogyakarta yang sekarang kita lihat telah banyak mengalami perubahan pada struktur konstruksinya. Sebelum runtuh akibat gempa bumi, Tugu Golong Gilig, bangunannya berbentuk silinder atau tabung dengan puncak berbentuk bola dan memiliki tinggi 25 meter. Bentuk Golong Gilig ini memiliki filosofi Manunggaling Kawulo Gusti yang mempunyai arti bersatunya antara rakyat dengan rajanya (penguasa). Sedangkan De witt Paal yang dibangun oleh pemerintah koloni Belanda di tahun 1889, memiliki puncak yang runcing dan tingginya dikurangi menjadi 15 meter. Pada tugu tersebut juga dicantumkan candra sengkala Wiwaraharja Manunggal Manggalaning Praja yang selain berarti tahun 1819, juga berarti pintu menuju kesejahteraan bagi para pemimpin Negara. Sangat jauh dari semangat yang tersirat pada bentuk Tugu yang lama. Itu dilakukan karena colonial Belanda untuk mengilangkan lambing persatuan yang ada dalam golong gilig demi tujuan politik devide-et-impera (politik pecah belah) pemerintah Hindia Belanda. Selain itu namanya pun diubah menjadi De Witt Pall atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia Tugu Pall Putih yang sekarang dikenal dengan Tugu Jogja.
Filosofi Tugu dan Lingkungan Sekitarnya dalam Budaya Jawa
Tugu Yogyakarta atau orang Jawa dulu biasa menyebutnya tugu golong-gilig, merupakan landmark Yogyakarta yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Monumen tugu ini terletak tepat ditengah garis lurus imajiner penghubung antara Kraton Yogyakarta, Marlioboro dan Gunung Merapi. Ada makna filosofis tersendiri dari posisi letak Tugu Yogyakarta hingga Kraton Yogyakarta, seperti jalan Mangkubumi (Jalan Margoutomo) yang terletak di selatan Tugu, membujur lurus sampai rel kereta api dengan dikelilingi oleh deretan toko dan hotel-hotel berbintang. Jalan Mangkubumi ini menyiratkan filosofi keutamaan hidup yang berpusat pada Tuhan. Bila Tuhan menjadi wacana kehidupan seseorang, maka berbagai ekspresi hidupnya tak jauh dari kemaslahatan dan cinta kasih tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, dan pembeda lain. Poros antara Tuhan dan manusia ini penting dalam peradaban Jawa karena Tuhan ialah faktor fundamental yang menciptakan dan mengatur kosmos.
Menyeberangi rel kereta api sampailah pada Jalan Malioboro yang membentang sampai Pasar Bringharjo. Malioboro terdiri atas dua kata, yaitu mali (wali) dan ngumboro (mengembara). Pesan tersiratnya, bila Tuhan telah diakui sebagai "causa prima", tugas manusia selanjutnya adalah menyebar kebaikan di muka bumi sebagaimana peran para wali 5 abad lalu. Setelah manusia mengutamakan kebaikan dan menyebarkan nilai-nilai moral, ia akan mencapai lapisan kemuliaan. Dimensi ini ditandai dengan Jalan Margomulyo (Pasar Bringharjo-Kantor Pos). Kemuliaan, dengan demikian, bukan sekadar posisi eksklusif di menara gading, melainkan suatu posisi kesadaran bahwa dunia adalah “panggung sandiwara” yang tak abadi, sehingga kemuliaan sejati terletak pada rahmat Tuhan. Tetapi, di atas kemuliaan, menurut filosofi jalan di Yogyakarta, masih terdapat satu langkah lagi sebelum mencapai keraton, yakni Jalan Pangurakan yang mencabang ke timur dan barat dengan alun-alun sebagai pemisahnya. Titik pangurakan itu meniscayakan manusia melepas kamuflase kepalsuan duniawi yang kini dikendalikan melalui tren dan label globalisasi (Pratama, 2018).
Letak Tugu Yogyakarta yang strategis, berada di perempatan jalan besar utama di Yogyakarta, yaitu yang membujur ke utara Jalan AM Sangaji, di selatan Jalan Pangeran Mangkubumi-Malioboro, disebelah timur Jalan Jenderal Sudirman dan ke arah barat merupakan Jalan Pangeran Diponegoro. Berdasarkan Morin (2014), bentuk Tugu pada saat ini persegi, di setiap sisinya terdapat prasasti yang menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam renovasi itu. Ketinggian Tugu saat ini dua belas meter di atas permukaan tanah akibat renovasi yang dilakukan terhadap tugu. Tugu mempunyai empat bentuk fisik, yaitu kotak berundak pada bagian bawah sebagai landasan, kotak dengan prasasti pada setiap sisinya, piramid tumpul dengan ornamen yang menempel pada setiap sisinya, dan puncak tugu berbentuk kerucut ulir. Bentuk-bentuk tersebut dikombinasi dengan hiasan-hiasan yang memiliki simbol Jawa seperti keris (Hasta Karya), panah, daun “waru”, daun loto, daun teratai, janget kinatelon, bentuk praba, bintang sudut enam, deretan titik atau ceceg, wajik, bentuk air tetes, dan setiliran. Selain itu, terdapat tulisan Jawa pada keempat sisinya. Warna yang tampak merupakan kombinasi cokelat hitam dan terdapat warna emas pada puncak Tugu Yogyakarta. Bentuk tugu secara geometris terdiri dari balok, prisma, dan untiran seperti kuncup. Pada bagian tubuh tugu terdapat prasasti tulisan Jawa dengan menggunakan warna cokelat.
Pergeseran makna Tugu Yogyakarta Dulu dan Sekarang
Kepercayaan Jawa atau Javanisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah satu atau merupakan kesatuan hidup. Javanisme memandang kehidupan manusia selalu terpaut erat dalam kosmos alam raya. Dengan demikian, kehidupan manusia merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan pengalaman yang religius (Morin, 2014:145). Manusia sebagai pusat dari sebuah budaya, yaitu sebagai pelaku budaya, memiliki beberapa penghayatan. Hal ini terwujud dalam berbagai alam pikiran orang Jawa yang merumuskan bahwa kehidupan manusia berada dalam dua kosmos (alam), yaitu makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos dalam pikiran orang Jawa adalah sikap dan pandangan hidup terhadap alam semesta yang mengandung kekuatan supranatural dan penuh dengan hal-hal yang bersifat misterius. Adapun mikrokosmos dalam pikiran orang Jawa adalah sikap dan pandangan hidup terhadap dunia nyata. Tujuan utama dalam hidup adalah mencari dan menciptakan keselarasan atau keseimbangan antara kehidupan makrokosmos dan mikrokosmos.
Dalam konteks mikrokosmos, tugu bermakna seseorang raja sebagai perwujudan Tuhan di dunia, merangkul dan mengajak masyarakatnya untuk selalu bersatu menghancurkan dan memusnahkan penjajahan. Hal ini dapat pula dimaknai sebagai penyatuan antara rakyat dengan Tuhan yang diwakili oleh raja. Dengan demikian, secara makrokosmos dan mikrokosmos, manunggaling kawulo lan Gusti bisa diartikan sebagai bentuk penyatuan antara rakyat, raja, dan Tuhannya. Konsep tersebut menjadi dasar filosofi makna Tugu Golong-Gilig. Belanda sangat takut dengan filosofi tersebut sehingga ketika membangun kembali tugu dibuat dalam bentuk seperti saat ini. Pemahaman-pemahaman itu oleh Belanda dihapuskan dan diganti dengan bentuk-bentuk prasasti yang bermakna kemuliaan hanya milik raja. Rakyat dan raja tidak lagi berjalan bersama menuju ke kemanunggalan, tetapi kesejahteraan dan kemanunggalan hanyalah milik raja (Morin, 2014:146).
Dari sejarah bentuk konstruksi tugu masa kini, mengingatkan penulis mengenai memori kolektif yang digagas oleh Abidin Kusno (2009) dalam bukunya yang berjudul “Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif Jakarta Pasca-Soeharto”. Dalam penjelasannya, Kusno membagi memori menjadi 5 tipologi, salah satunya tipologi memori kolektif. Tipologi memori kolektif adalah memori yang tak terwadahi. Memori disini sering tidak mendapat tempat diruang publik karena dianggap tidak sejalan dengan memori resmi atau karena terlalu besar sehingga tidak ada yang mampu mewadahinya. Ia sering terjebak antara pengingatan atau pelupaan dan sering timbul dari pengalaman kekerasan. Misalnya tentang kerusuhan Mei seringkali dianggap lebih baik untuk dilupakan karena meninggalkan memori yang menyakitkan juga cermin buruknya sejarah mentalitas Indonesia. Tetapi disisi lain usaha-usaha melupakan ini terkadang justru memberi kesempatan bagi pengulangan peristiwa pahit itu sendiri.
Penulis menambahkan jika tanpa adanya monumen, sejarah, dan ruang publik yang menjadi saksi peristiwa tersebut maka masyarakat justru membentuk serta menyimpan memori kolektif diruang-ruang pribadi mereka. Kusno (2009) juga mencontohkan dalam ruang publik ini memori kolektif terbentuk atas dasar kesengajaan. Pemerintah atau otoritas yang berwenang menjadi salah satu pihak yang bisa mengatur memori kolektif ini. Pada zaman Jepang misalnya, untuk membentuk memori baru maka mereka memisahkan diri dari memori lama penjajahan Belanda dengan cara menghilangkan simbol-simbol kejayaan Belanda seperti penurunan patung Jan Pieteerzoon atau dengan mengubah Villa Isola yang merupakan simbol arsitektur modernis Belanda menjadi Museum Mengenang Perang Pembebasan Tanah Jawa.
Dalam kasus ini, untuk menghilangkan kepercayaan antara rakyat pribumi terhadap rajanya, terdapat tujuan tersirat pemerintah kolonial Belanda yang merekonstruksi tugu setelah tugu yang lama runtuh akibat gempa bumi yaitu untuk memecah belah persatuan antara rakyat pribumi dan penguasanya atau bisa dikenal sebagai pelaksanaan politik devide et impera (politik pecah belah) untuk menguasai Yogyakarta masa itu. Pembangunan monumen tugu ini juga untuk meningkatkan citra pemerintah kolonial Belanda di mata para penguasa Yogyakarta namun secara tidak langsung mendekonstruksi makna yang tersirat dalam monumen tugu yang lama. Monumen tugu yang dibangun oleh Belanda ini menyimpan memori kolektif tentang perjuangan rakyat pribumi dan rajanya dalam mempertahankan wilayah pemerintahan dan juga makna sebenarnya dari tugu itu sendiri.
Bergesernya makna pada Tugu Yogyakarta juga berpengaruh pada kesakralan bangunan itu sendiri. Pada masa ini pun, monumen tugu yang awalnya sebagai patokan arah Gunung Merapi bagi para raja untuk bersemedi, sekarang dikomodifikasikan untuk kepentingan wisata. Pada malam hari, Tugu sering dijadikan tempat berfotofoto ataupun duduk-duduk meskipun telah diberi peringatan untuk tidak duduk-duduk di kaki bawah Tugu ataupun mencoret-coret Tugu. Menurut Djatiningrat, Pengagem Tepas Dwarapura Ngayogyakarta Hadingrat (Morin, 2014:147) tugu saat ini berbeda makna dengan Tugu Golong-Gilig. Saat ini lebih kepada kesejahteraan yang ditujukan hanya bagi raja dan bukan lagi untuk raja dan rakyatnya. Filosof manunggaling kawula lan Gusti telah hilang dan tidak tercermin pada tugu saat ini. Sehingga bagi Keraton, tugu saat ini tidak bermakna. Tugu bukan lagi menjadi salah satu simbol keraton tetapi lebih pada ikon Kota Yogyakarta saja.
Esai Tanggapan 1
Oleh: Reza Altamaha
Berbicara mengenai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal yang terlintas ketika membicarakannya adalah budaya dan masyarakatnya. Secara geografis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta terletak antara 07°15'24" - 07°49'26"LS dan 110°24'19" - 110°28'53"BT. Daerah Istimewadengan motto “Hamemayu Hayuning Bawana” tersebut di bagian selatannya dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat dan barat laut dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi: Kabupaten Klaten disebelah Timur Laut, Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara, Kabupaten Purworejo di sebelah Barat, dan Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut (Humanitarian Response, 2012). Pusat dari Yogyakarta, yakni Kota Yogyakarta juga menyimpan potensi yang beragam.
Esai pertama yang dituliskan oleh Hanna Rahmayani Wisnuputri berusaha memaparkan mengenai keberadaan Tugu Yogyakarta, Wisnuputri membuka esainya dengan membawakan situasi seputar tugu tersebut. Ia menangkap keberadaan bangunan-bangunan yang mengitari tugu. Lokasi berdirinya Tugu Pal Putih memang tidak sembarangan, dalam konteks masa kini – tugu memang dikelilingi bangunan-bangunan modern seperti pusat perbelanjaan dan tempat nongkrong berupa kafe atau restoran yang dekat dengan kehidupan masyarakat urban. Disamping itu, keberadaan bangunan-bangunan lawas atau kuno juga masih dapat ditemui di sekitar tugu. Tidak jauh dari tugu Yogyakarta, di sisi selatan monumen tersebut terdapat sebuah jalan yang juga menjadi salah satu ikon Yogyakarta, yakni Jalan Malioboro. Di sepanjang jalan itu berdiri bangunan-bangunan klasik seperti N.V. Boekhandel en Drukkerij Kolff-Bunning (Jogja Library Center), Gedung Residen (Gedung Agung), Benteng Rustenberg (Benteng Vredeburg), dan Kampung Ketandan.
Tugu Pal Putih juga tidak hanya menjadi sekedar ikon yang juga menjadi logo bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena kerap juga dijadikan sebagai ruang publik untuk kegiatan lintas kepercayaan, seperti doa bersama maupun aksi bisu. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah aksi solidaritas, doa dan orasi perdamaian terkait tragedi bom Surabaya yang diikuti oleh berbagai elemen agama seperti dari Forum Jogja Damai, Gusdurian Jogja, Srikandi Lintas Iman, Young Interfaith Peacemake Community (YIPC), Angkatan Muda Ahmadiyah Indonesia dan aliran kepercayaan yang menggambarkan kebhinekaan di Indonesia, Minggu malam, 13 Mei 2018 (bernas.id, 2018).
Selain itu, terdapat pula aksi rutin mingguan yang dilaksanakan di Tugu Yogyakarta. Kegiatan tersebut bernama Aksi Kamisan yang memang dilakukan rutin setiap kamis sore dan tidak hanya di Yogyakarta saja. Aksi “Kamisan” selalu konsisten mengusung isu-isu yang terkait dengan HAM, lingkungan dan lain-lain. Aksi tersebut memiliki sebuah jargon yang sering diucapkan beberapa peserta aksi “Kamisan” di Yogya, yakni “merawat ingatan, melawan impunitas”. Jargon atau kalimat tersebut terus disuarakan bertujuan untuk mengingatkan kita atas pelanggaran HAM yang terjadi era orde baru hingga reformasi saat ini (Setyawan, 2019). Dengan diadakannya kegiatan maupun aksi yang berlatar di Tugu Pal Putih, menjadikan bangunan tersebut bukan hanya sebagai bangunan yang dekat dengan konteks wisata seperti yang sekarang terjadi. Tugu seakan telah menjelma menjadi ruang publik yang seharusnya dimiliki atau dapat dipergunakan oleh semua pihak.
Esai sebelumnya membahas dengan cukup baik beberapa hal terkait Tugu Yogyakarta, seperti daya tarik Tugu Yogyakarta, sejarah Tugu Yogyakarta, Filosfi Tugu dan lingkungan sekitarnya dalam Budaya Jawa, serta pergeseran Tugu Yogyakarta dulu dan sekarang. Berkenaan dengan itu, saya menaruh perhatian pada bahasan mengenai sejarah Tugu Yogyakarta. Kendati pembahasan tersebut cukup baik, saya pikir diperlukan penjabaran yang lebih mendalam lagi mengenai pendirian tugu tersebut berkaitan juga dengan sejarahnya dari masa ke masa. Satu hal lagi, penting kiranya untuk membahas mengenai situasi sosial masyarakat Yogyakarta kala tugu dibangun beserta peristiwa-peristiwa yang belum disajikan di tulisan sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam esai tanggapan ini fokusnya akan berkutat pada sejarah Tugu Yogyakarta.
Menilik Sejarah Tugu Yogyakarta
Berbicara mengenai suatu kota, maka tidak lepas dengan keberadaan landmark yang menjadi penanda khas bagi suatu kota. Berpijak pada hal itu, penulis berusaha memperdalam pembahasan mengenai Tugu Yogyakarta yang telah dibahas dalam esai sebelumnya. Tugu tersebut dapat ditemui di persimpangan antara Jalan Margo Utomo (dulu dikenal dengan Jalan Pangeran Mangkubumi), Jalan A.M. Sangaji, Jalan Jendral Sudirman, dan Jalan P. Diponegoro. Tugu ini berada di utara keraton, menjadi bagian dari sumbu filosofis yang membentang dari Gunung Merapi, Tugu Golong Gilig, Keraton Yogyakarta, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan. Karena bentuknya yang panjang dan warnanya yang putih, orang Belanda menyebutnya sebagai white paal (tiang putih). Oleh sebab itu hingga kini, Tugu Yogyakarta atau Tugu Golong Gilig kadang masih disebut sebagai Tugu Pal Putih (Kraton Jogja, 2018).
Sejarah pendirian Tugu Yogyakarta tidak bisa lepas dari peran Sultan Hamengkubuwono sebagai pemrakarsa pendirian monumen tersebut. Sultan Hamengkubuwono I, dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi – pendiri sekaligus pembangun Keraton Yogyakarta ini lahir pada tanggal 5 Agustus 1717 dengan nama Bendara Raden Mas (BRM) Sujono (Kraton Jogja, 2019). Pangeran Mangkubumi merupakan putra Sunan Amangkurat IV melalui garwa selir yang bernama Mas Ayu Tejawati.
Pasca Perjanjian Gianti pada tanggal 1755. Perjanjian Giyanti merupakan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 (Kemis Kliwon, 12 Rabingulakir 1680 TJ) dan menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Paku Buwono III, sementara Ngayogyakarta – atau lazim disebut Yogyakarta – dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I (Kraton Jogja, n.d.). Pangeran Mangkubumi dan Garwa Selir Mas Ayu Tedjawati diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Beliau kemudian membuka hutan di Pabringan untuk dijadikan Ibukota kerajaan. Di dalam hutan itu ada pesanggrahan yang bernama Ngayogya, yang merupakan tempat istirahat membawa jenazah dari Surakarta ke Imogiri. Ketika Kraton selesai dibangun kemudian diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat (Heru, 2018). Pada tanggal 7 Oktober 1756 Sultan Hamengkubuwono I pindah dari Kebanaran ke istana yang baru di Ngayogyakarta.

Sultan Hamengkubuwono I juga merupakan seorang Jawa yang menjunjung tinggi makna dan perlambang. Setahun setelah pindah ke keraton, Hamengkubuwono I lalu membangun sebuah Tugu di utara keraton (Heru, 2018). Tugu ini terletak dalam satu garis lurus dan dengan keraton. Tugu yang dibangun menjadi titik dari garis lurus di utara, Keraton di tengah dan paling selatan adalah Panggung Krapyak. Nurhajarini dkk (2012) dalam Sumintarsih dan Ambar Adrianto (2014, p. 19) menjelaskan bahwa Panggung Krapyak apabila diteruskan ke selatan akan sampai Pantai Selatan Samudera Hindia. Dari Tugu pal putih bila diteruskan akan sampai ke Gunung Merapi. Tempat-tempat dalam sumbu filosofis tersebut merupakan lokasi-lokasi penting dalam struktur kebudayaan kraton dan masyarakat. Dimulai dari jalur itulah awal pertumbuhan Kota Yogyakarta dan kemudian berkembang ke arah timur-barat tatkala jaringan transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya berkembang.
Pada saat awal berdirinya, tugu tersebut secara tegas menggambarkan Manunggaling Kawula Gusti, semangat persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajahan. Semangat persatuan atau yang disebut golong gilig itu tergambar jelas pada bangunan tugu, tiangnya berbentuk gilig (silinder) dan puncaknya berbentuk golong (bulat), hingga akhirnya dinamakan Tugu Golong-Gilig (Haryono, 2015, p. 99). Sri Sultan Hamengkubuwono I jugalah mengajarkan falsafah golong gilig manunggaling kawula Gusti (hubungan yang erat antara rakyat dengan raja dan antara umat dengan Tuhan) serta Hamemayu Hayuning Bawono (menjaga kelestarian alam) (Kraton Jogja, 2019). Keberadaan Tugu ini juga sebagai patokan arah ketika Sri Sultan Hamengkubuwono I pada waktu itu melakukan meditasi, yang menghadap puncak Gunung Merapi. Bangunan Tugu Jogja saat awal dibangun berbentuk tiang silinder yang mengerucut ke atas, sementara bagian dasarnya berupa pagar yang melingkar, sedangkan bagian puncaknya berbentuk bulat. Ketinggian bangunan tugu golong gilig ini pada awalnya mencapai 25 meter (Haryono, 2015, p. 99).
Tugu Golong Gilig Pasca Gempa 1867
Keberadaan Tugu Golong Gilig berubah tatkala terjadi gempa bumi hebat pada 10 Juni 1867 yang mengguncang Yogyakarta – Gempa yang terjadi turut merusak bangunan penting kala itu, seperti Gedung Residen (Gedung Agung) dan Benteng Rustenberg (Benteng Vredeburg). Tahun 1989, Renovasi Tugu dilaksanakan berdasarkan titah Sri Sultan Hamengkubuwono VII, yang ditandai dengan candra sengkala Obah Trus Pitung Bumi. Pembangunan kembali tugu tersebut mendapat dukungan dari Residen Belanda Y. Mullemester, dengan arsitek perencana YPF Van Brussel dan dibiayai oleh Pepatih Dalem Kanjeng Raden Adipati Danureja V (Heru, 2018). Sayangnya perombakan total menyebabkan bentuk tugu tidak lagi Golong Gilig – dampaknya pun mengikis makna persatuan antara penguasa dan rakyat yang disimbolkan dengan Golong Gilig yang kini tinggal kenangan (Kurniawan, 2015).
Renovasi Tugu mengahasilkan bentuk persegi dengan tiap sisi dihiasi semacam prasasti yang menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam renovasi itu. Bagian puncak tugu tak lagi bulat, tetapi berbentuk kerucut yang runcing. Ketinggian bangunan pun menjadi lebih rendah, yakni hanya setinggi 15 meter atau 10 meter lebih rendah dari bangunan semula (Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2018). Sejak saat itulah, tugu ini disebut sebagai De White Paal atau Tugu Pal Putih. Dibalik itu pun ada taktik terselubung dari pemerintah kolonial yang merasa khawatir akan persatuan penguasa dan rakyat yang disimbolkan oleh Tugu Golong Gilig.
Memaknai Keberadaan Tugu Yogyakarta
Dijelaskan bahwa Tugu Yogyakarta bukan hanya sebagai tengaran atau landmark Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) – Tugu tersebut dibangun dengan simbol-simbol yang memiliki pesan mendalam terutama soal relasi dan kesatuan antara penguasa yakni Sri Sultan Hamengkubuwono dengan rakyatnya. Namun begitu, dengan dinamika yang terjadi – Tugu tak luput mengalami perubahan yang ditunjukkan dari bentuknya yang berubah setelah renovasi dikarenakan bencana gempa bumi yang terjadi.
Analisis menarik mengenai Tugu Yogyakarta disampaikan oleh Laksmi Kusuma Wardhani (2008), sebagai berikut:
“Pal Putih monument symbolizes two ways in creating the transcendent-immanent. Immanent goes toward The Great Unity and transcendent spreads, flows, being the immanent antagonistic and dualistic pair. The horizontal side (wordly) spread wider and more complex. The vertical side (spiritual) goes higher toward the center, showing wider authority. The center of Pal Putih is high level paradox, becoming axis mundi of community that connects the worldly and spiritual needs, results in the blend of all opposing substanstial pairs. The existing vertical relation has world and universe elements, and at the end horizontally human finds dialog and reconfirmation with his self activities and material needs he should gain. Instinctly, it is related to the dunia bawah (the life after) and dunia atas (heavenly world)”. (Wardani, 2008, p. 5)
Menanggapi pernyataan Wardani, Tugu Yogyakarta sebagai suatu monumen yang diprakarsai Sri Sultan Hamengkubuwono I disisipkan falsafah Manunggaling Kawula Gusti yang diartikan sebagai persatuan dan kesatuan. Kawula berarti Rakyat dan Gusti yang berarti pimpinan. Falsafah tersebut memberikan makna bahwa rakyat sebagai pimpinan dan Gusti yang merupakan Sang Pencipta (Tuhan). Pesan tersebut memperlihatkan bahwa pemimpin kala itu berupaya untuk menyatukan rakyat dengan penguasa melalui simbolisasi yang dibangun lewat suatu monument, yakni Tugu Yogyakarta. Meskipun Tugu yang hampir berumur tiga abad ini telah berubah bentuknya, makna dan memori yang tersimpan didalamnya patut untuk diingat. Masyarakat perlu diingatkan lagi tentang arti penting yang melatarbelakangi berdirinya Tugu tersebut.
Esai Tanggapan 2
Oleh: Lowa Satada
Telah disampaikan pada tulisan diatas jika Tugu Yogyakarta yang merupakan salah satu ikon kota Yogyakarta memiliki daya tarik diantaranya dari aspek sejarah hingga filosofinya. Esai yang ditulis oleh Hanna Rahmayani Wisnuputri telah baik dalam mengkaji perubahan-perubahan pemaknaan Tugu Yogyakarta dari dulu hingga sekarang, akan tetapi pembahasan yang diberikan lebih condong dari segi historis dan monumentalnya saja. Sementara kita agaknya juga perlu untuk membahas pergeseran makna yang ada dari Tugu Yogyakarta terkait dengan aspek kepariwisataannya. Layaknya sebuah bangunan monumental Tugu Yogyakarta memiliki fungsi seperti yang dikatakan oleh Abidin Kusno dalam bukunya yaitu untuk menyimpan memori, “…objek atau bangunan bisa menyimpan memori, suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia karena usianya yang lebih pendek. Asumsi ini juga berangkat dari keinginan untuk menstabilkan memori dengan bantuan objek yang diharapkan mampu bertahan selama-lamanya”.
Tetapi perlu kita pertanyakan lagi apakah hingga saat ini fungsi Tugu Yogyakarta masih demikian? Siapakah yang hingga saat ini masih memiliki memori itu? Mengingat sudah sangat tuanya usia Tugu Yogyakarta itu sendiri kita patut mempertanyakan ulang apakah masyarakat benar-benar memaknai Tugu Yogyakarta ini sebagai alat pembangun memori kolektif mereka. Disini sebagian masyarakat mungkin masih merasakan hal tersebut, tetapi jika kita membahas mengenai generasi saat ini khususnya para anak muda misalnya apakah Tugu Yogyakarta ini berhasil membangkitkan memori kolektif mereka mengingat generasi ini terkadang tidak mengetahui makna pembangunan Tugu itu sendiri seperti sejarah atau filosofi Tugu tersebut. Yang mungkin mereka ketahui dan perhatikan mungkin hanyalah terkait Tugu Yogyakarta sebagai ikon wisata kota Yogyakarta. Sehingga pada bagian ini saya akan berkutat pada perubahan makna Tugu Yogyakarta menjadi spot pariwisata yang digandrungi wisatawan baik dalam maupun luar daerah.
Terdapat beberapa hal yang mendukung berubahnya makna Tugu Yogyakarta atau Tugu Pal Putih yang mulanya sebagai monumen sejarah menjadi spot pariwisata. Faktor utama yang mendukung hal tersebut adalah karena lokasi keberadaan Tugu itu sendiri yaitu di Kota Yogyakarta yang pada hakikatnya telah dikenal sebagai salah satu kota yang menjadi destinasi wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Syakdiah (2017) mengungkapkan jika kondisi sebagian besar masyarakat Yogyakarta yang masih memegang teguh adat istiadat Jawa menjadikan keunikan tersendiri di tengah kemajuan zaman yang pesat ini. Harmonisasi antara sejarah, kebudayaan dan tradisi menjadi nilai jual dari Kota Yogyakarta itu sendiri. Selain itu kondisi alamnya juga menjadi daya tarik tersendiri seperti banyaknya pantai, gunung, warisan-warisan sejarah seperti candi, monument, museum hingga kekhasan kuliner ikut mendukung Yogyakarta sebagai kota pariwisata.
Bagaimana kita memaknai Tugu Yogyakarta sekarang?
Manusia dalam hidup ini memiliki usia yang terus bertambah hingga pada puncaknya yaitu kematian. Tugu Yogyakarta pun demikian, semakin harinya semakin menua hanya saja ia tidak memiliki batas kematian atau hilang selama bangunan itu masih tetap berdiri kokoh. Itu jika dilihat dari segi bangunan fisiknya. Saya disini mengajak untuk merenungkan lalu bagaimana dengan nilai-nilai historis Tugu Yogyakarta itu, apakah ia akan ikut menua dan hingga pada titik tertentu luntur karena tak ada ada yang mampu mengingat memori dari Tugu Yogyakarta tersebut juga tak ada yang memiliki minat pada sejarah dari bangunan itu sendiri?
Ketika kita membicarakan Tugu Yogyakarta maka seringkali yang terngiang dalam pikiran kita hanya lah seputar pesona malam di sekitar kawasan Tugu. Sorot-sorot lampu jalanan yang remang-remang menambah kesan klasik nan romantis di area Tugu Yogyakarta ini. Sementara itu kondisi ini sangat berbeda dengan disiang hari. Kondisi cuaca kota Yogyakarta di siang hari yang lumayan panas menyebabkan orang enggan untuk menyambangi kawasan ini mengingat tidak adanya tempat berteduh yang disediakan disana juga letaknya yang berada tepat di tengah jalan menjadikan orang terlalu malas mendekat juga karena volume kendaraan yang melintas cukup tinggi disiang hari.
Kondisi area Tugu Yogyakarta di malam hari dan siang hari (sumber: www.pexels.com dan https://commons.wikimedia.org)
Tugu dengan keunikannya entah itu didukung oleh sejarah, filosofis, atau arsitekturnya nyatanya berubah dari sekedar monumen pengingat menjadi daya tarik wisata. Para wisatawan baik di dalam maupun luar kota ketika mengunjungi kota Yogyakarta kebanyakan memasukkan Tugu Yogyakarta kedalam list tempat yang akan mereka kunjungi. Karena telah berubah menjadi objek wisata maka kegiatan yang ada diarea Tugu Yogyakarta ini sangatlah beragam. Aktivitas yang dominan dilakukan oleh para wisatawan tentunya adalah berfoto untuk mengabadikan momen atau sebagai bukti jika mereka ada di Yogyakarta. Beberapa kemudian juga bisa menghabiskan waktu sambil menikmati suasana di sekitar area Tugu sambil berbincang-bincang kecil bersama sanak saudara, kerabat atau sahabat. Kondisi keramaian ini pun kemudian sering dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk menjajakan jasa atau barang dagangan seperti jasa parkir, berjualan rokok, rumah makan, makanan-makanan ringan, dan semacamnya. Dan mungkin inilah sama seperti tujuan awal pengembangan pariwisata Yogyakarta yaitu untuk meningkatkan perekonomian khususnya perekonomian masyarakat setempat.
Memasarkan Sejarah
Sejarah telah menjadi daya tarik yang dihadirkan oleh Tugu Yogyakarta atau Tugu Pal Putih itu sendiri yang kemudian mengubahnya menjadi spot wisata khususnya wisata edukasi yaitu yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada wisatawan, pengetahuan disini jika dalam konteks Tugu Yogyakarta adalah terkait pengetahuan sejarah. Sehingga kita disini mungkin lebih mudah menyebutnya sebagai wisata sejarah. Tetapi yang perlu kita perhatikan disini adalah terdapat karakteristik yang berbeda antara Tugu Yogyakarta sebagai bangunan sejarah dengan Tugu Yogyakarta sebagai area wisata.
Ketika ia kita tempatkan pada wacana fisiknya yaitu bangunan ia sebatas pada alat untuk menyimpan memori akan suatu peristiwa sejarah. Tetapi ketika kita menempatkannya sebagai objek wisata maka pembicaraan kita akan beralih ke seputar masalah ekonomi. Hal ini karena pariwisata sendiri entah itu dikatakan sebagai wisata edukasi, wisata sejarah, wisata budaya, dan sebagainya ujung-ujungnya tetap berorientasi pada masalah ekonomi. Sejarah disini kemudian adalah modal ekonomi itu sendiri untuk Tugu Yogyakarta tersebut. Kita bisa memetik beberapa manfaat dari sini dimana dengan keberadaan Tugu Yogyakarta kita tidak hanya bisa melestarikan sejarah budaya kita tetapi sekaligus memetik keuntungan ekonomis khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Tugu ini misalnya dengan menyediakan jasa layanan parkir, rumah makan, maupun berdangan makanan-makanan ringan dan sebagainya.
Menjual nilai sejarah dari sebuah tempat tentunya bukan hal yang asing bagi kita. Kekayaan sejarah dan budaya Indonesia sangatlah besar untuk itu agaknya tidak mungkin kita hanya sekedar menyimpannya tetapi harus mengambil keuntungan-keunntungan darinya khususnya keuntungan ekonomi. Abidin Kusno (2009) dalam bukunya telah memberikan contoh terkait hal ini yaitu tentang memasarkan memori dengan mengambil contoh pengembagan kota tua Jakarta sebagai “Koridor Kota Joang” dimana tidak hanya berupaya untuk menciptakan memori kolektif bagi warga kotanya tetapi juga membangkitkan ekonomi dengan memanfaatkan tema “warisan” sejarah (heritage). Ia menambahkan jika “… proyek yang mengangkat tema sejarah ini menunjukkan kepada kita suatu wacana memori yang berasal dari ambisi untuk membangkitkan kekuatan ekonomi dengan cara memasarkan kisah dari situs masa lalu”(2009:25).
Tugu Yogyakarta disini pun demikian dimana ia menjajakan kekhasan nilai sejarah dan budayanya untuk memperoleh manfaat ekonomi. Suyatmi Waskito Adi dan Edy Purwo Saputro (2017) menyatakan jika daerah tujuan wisata berbasis sejarah budaya merupakan perpaduan antara dua bentuk daya tarik wisata yaitu antara objek yang tumbuh alami dan objek wisata yang tumbuh melalui proses penciptaan dengan mengacu pada aspek modernisasi. Jika dengan Tugu Yogyakarta? Apakah ia juga memiliki dua unsur tersebut?. Menurut saya mungkin bisa demikian. Jika dikatakan sebagai objek yang tumbuh alami, memang Tugu Yogyakarta pada awal pembentukannya tentunya tidak pernah memikirkan jika nantinya ia akan menjadi objek wisata atau ikon kota Yogyakarta itu sendiri. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu karena kekayaan filosofis serta sejarahnya maka memicu orang untuk penasaran dan mengunjunginya, lambat laun ketertarikan ini bertambah banyak dan mau tak mau ia berubah menjadi objek wisata itu sendiri.
Tetapi disisi lain Tugu Yogyakarta juga bisa dikatakan tumbuh melalui penciptaan yang disengaja. Tugu Yogyakarta dalam hal ini sengaja dihadirkan sebagai maskot kota Yogyakarta. Tidak bisa kita pungkiri jika branding menjadi hal penting yang harus diperhatikan untuk mendukung kelancaran pengembangan pariwisata disebuah daerah. City branding menurut Abdurrahman (2015) merupakan “upaya yang dilakukan para perencana perkotaan untuk menciptakan kota yang sesuai dengan potensi dan mengakomodasi penduduk lokalnya sehingga dapat menjadi kota yang layak huni”. Selain itu keuntungan dari city branding juga tentang bagaimana sebuah kota bukan lagi dilihat menjadi hanya sekedar lokasi namun lebih menjadi tujuan destinasi.
Di Yogyakarta sendiri kita mengenal istilah “Jogja Istimewa” sebagai tagline dari kota ini. Untuk menciptakan branding tersebut tentunya harus dipikirkan terlebih dahulu apa yang benar-benar menjadi istimewa dari kota Yogyakarta ini pastinya. Tugu Yogyakarta menjadi salah satu modal dari penyuksesan upaya branding tersebut. Jika kita perhatikan pasti dalam setiap promosi pariwisata Yogyakarta seperti lewat tayangan video, majalah, koran, stiker, hingga aksesoris-aksesoris pasti kita akan menemui adanya gambar Tugu Yogyakarta atau Pal Putih ini menyertainya. Tugu Yogyakarta disini sengaja ditampilkan untuk memvisualkan kota Yogyakarta kepada dunia luar, karena Tugu tersebut selain menyimpan makna sejarah juga banyak memasukkan unsur-unsur filosofi Jawa dalam arsitekturnya yang mampu memikat mata dunia.
Esai Replay
Oleh: Okky Chandra Baskoro
Citra dan makna yang terbentuk dari sebuah kota kini berkembang dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor didalamnya. Perkembangan makna dan citra sebuah kota yang fokus dari tulisan ini menjadi penting untuk dibahas secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai perspektif khususnya antropologi. Kajian antropologi digunakan untuk melihat secara lebih mendalam mengenai dinamika yang terjadi dari terbentuknya proses pemaknaan yang juga berkaitan dengan terbentuknya citra dalam masyarakat. Monumen adalah sebuah bentuk perwujudan dari memori kolektif masyarakat yang memang difungsikan sebagai sebuah penanda kejadian-kejadian tertentu yang pernah terjadi di masyarakat suatu daerah. Dengan fungsi penanda tersebut kelestarian sebuah monument sebagai sebuah monument perlu dijaga kelestarian dan keberlangsungannya baik secara fisik maupun sosial di dalam masyarakat. Tugu Yogyakarta yang memiliki berbagai perspektif dalam memaknai eksistensinya menjadi sebuah contoh konkret upaya antropologi untuk berkecimpung dalam studi perkotaan.
Perkembangan studi perkotaan di Indonesia yang khusus berfokus pada memori kolektif dipelopori oleh Abidin Kusno dalam melihat perubahan yang terjadi di Jakarta pada beberapa waktu temporal. Dengan mengambil konsep kajian yang sudah dimulai oleh Abidin Kusno, penulisan keempat esai ini menjadi sebuah latihan atau percobaan untuk ikut menelisik secara lebih mendalam mengenai perubahan makna dan konteks sosial-budaya dalam melihat perubahan pemaknaan terhadap memori kolektif khususnya dikalangan anak-anak muda dan wisatawan. Pertanyaan bagaimanakah pemaknaan yang kini dilakukan oleh masyarakat khususnya kalangan muda dan wisatawan dalam melihat Tugu Yogyakarta? Tugu Yogyakarta sebagai sebuah monumen yang dibangun dan kaya akan makna filosofis dan sejarah dibaliknya kini tidak dapat dilihat dari perspektif ini saja. Keberadaan Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata bagi wisatawan baik dalam maupun luar negeri menjadikan perspektif pariwisata menjadi penting untuk diperhatikan dalam pembahasan. Tugu Yogyakarta yang dikonstruksikan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai ikon kota atau landmark telah melahirkan berbagai pemaknaan bergantung pada konteks yang dianut masyarakatnya.
Setelah membaca dan mencerna isi dari masing-masing tanggapan terhadap esai pertama yang dituliskan oleh Hanna Rahmayani Wisnuputri, terdapat beberapa poin penting mendukung dan menambahkan bahkan memperlengkap narasi pemaknaan Tugu Yogyakarta. Kedua penganggap Reza Altamaha dengan memberikan narasi historis yang mengkhususkan pada konteks sosial dibalik pembangunan Tugu dan Lowa Satada yang menyajikan perspektif pariwisata sebagai bagian dari kajian kontemporer dalam melihat pemaknaannya. Usaha kedua penganggap yang menghadirkan eksplanasi secara utuh dari kedua perspektif tersebut perlu diapresiasi dan dimaknai kehadirannya untuk mempertajam analisis seputar pemaknaan dari Tugu Yogyakarta pada saat ini.
Kembali ke Sejarah
Konteks sosio-historis dari Tugu Yogyakarta dan berbagai nilai-nilai budaya dan filosofi menjadi sebuah ciri khas tersendiri hampir pada seluruh bangunan budaya yang berada di Yogyakarta pada umumnya. Pendirian Tugu Yogyakarta yang memang sejak awal dibangun sebagai sebuah landmark atau penanda kota memiliki pemaknaan secara tersendiri. Bentuk bangunan fisik yang mengalami perubahan juga diikuti dengan adanya perubahan makna dan filosofi dari segi bentuk. Kentalnya filosofi jawa dalam memaknai bentuk, rupa, dan warna dari suatu bangunan menjadikan sebuah kekhasan tersendiri dari bangunan Jawa (Endraswara, 2015). Dasar pemahaman budaya dan filosofi lokal yang memberikan suatu ciri khas tersendiri dalam bentuk bangunan atau dalam konteks ini dapat disebut sebagai sebuah artefak di tengah kehidupan Kota Yogyakarta yang makin ramai akan aktivitas manusia.
Bangunan budaya yang kini dikelompokkan sebagai cagar budaya termasuk didalamnya kantor pemerintahan, museum, dan monumen kini mulai banyak dialihfungsikan sebagai kawasan historis yang terdapat regulasi ketat dalam menjaga kelestariannya. Untuk menjaga bangunan cagar budaya sekaligus mengelola keberlanjutannya banyak dari bangunan-bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan manusia seperti museum, kantor pemerintahan, maupun sekolah. Daerah pusat kota Yogyarakarta yang memiliki berbagai macam bangunan Belanda dan bangunan budaya menjadi sebuah ciri khas tersendiri yang membentuk serta menguatkan aspek historis sebagai faktor pembentuk citra Yogyakarta sebagai kota sejarah. Pentingnya peranan historis dalam membentuk arsitektur dan citra kota sendiri juga diakibatkan karena posisi Yogyakarta yang secara historis termasuk penting dalam perjuangan kemerdekaan. Pembangunan berbagai monumen adalah sebuah bentuk mewujudkan memori kolektif di masyarakat dan juga berfungsi untuk sarana mengingat suatu kejadian yang pernah dialami (Ahimsa-Putra, 2001).
Kaitan yang kuat mengenai sejarah dalam pembentukkan sebuah kota memang menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Kajian perkotaan kini telah mengundang masuknya ilmu sosial yang lebih menitikberatkan pada perspektif sosiologi dan antropologi untuk melihat dinamika masyarakat yang menjadi sebuah faktor pendukung perubahan menjadi penting untuk diperhatikan. Masuknya ilmu sosial humaniora dalam mengkaji kota yang lebih banyak dikaji oleh ilmu arsitektur dan perencanaan kota mulai muncul dengan dipeloporinya usaha Boyer dalam melihat perubahan kota. Pada beberapa kajian perkotaan kontemporer yang berusaha untuk melihat keterkaitan antar faktor dalam kehidupan kota dalam melihat fenomena perubahan kota khususnya yang terjadi saat ini.
Perubahan sebuah kota yang dapat diamati melalui pergerakan atau dinamika masyarakat melalui tiga macam gerakan yakni dari ‘bawah’, ‘tengah’, dan ‘atas’ (Loughran, et al., 2015). Kevin Loughran dkk berpendapat bahwa memori sosial secara kolektif memiliki peranan penting dalam menentukan arah perubahan yang terjadi di kota. Memori sosial yang terkumpul dan dimaknai dan dijadikan sebagai memori kolektif memiliki fungsi sebagai memori bersama (share memories) dan juga menjadi penentu pembangunan. Dinamika masyarakat kota yang secara struktural terbagi menjadi tiga golongan sesuai dengan pembagian berdasarkan oleh Kevin Loughran dkk, menunjukkan andil besar masyarakat dalam pembentukkan sebuah kota. Sejarah kota yang menjadi diisi dengan kisah pergerakan sosial diantara ketiga kelompok menghasilkan sebuah relasi kuasa yang mempengaruhi kebijakan pembangunan kota.
Menilik kasus di Yogyakarta pelaksanaan pembangunan dan tata kota dipegang oleh kalangan atas yang dalam hal ini adalah orang-orang yang masuk kedalam bagian dari keluarga Kraton Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih menganut sistem kerajaan dalam struktur pemerintahannya pada saat awal terbentuknya, menyebabkan kepemilikan lahan disebagian besar wilayah pusat kota atau dekat Kraton masih dimonopoli oleh kalangan keluarga sendiri. Pembangunan daerah pusat Yogyakarta termasuk kawasan Tugu, Malioboro, hingga jalan menuju Kraton menonjolkan nilai-nilai budaya dari segi arsitektur yang bergaya khas dan jarang untuk lepas dari pandangan mata. Setiap elemen dalam pembangunan yang dilakukan atas perintah Raja Yogyakarta saat itu sangat lekat dengan dilabelinya pemaknaan terhadap komponen-komponennya.
Tugu Yogyakarta yang menjadi ikon kota bahkan provinsi ini memiliki bentuk dan pemaknaan secara filosofis yang dianut oleh pemerintah maupun masyarakat lokal dengan berbeda. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta menggunakan tugu sebagai salah satu komponen logo daerah memaknainya sebagai sebuah penanda atau ciri khas bagi daerah tersebut. Meski sama-sama menggunakan lambang Tugu Yogyakarta sebagai bagian dari logo, terdapat corak yang berbeda dari penggambarannya. Pada logo provinsi tugu digambarkan dengan bagian puncak berbentuk kuncup bunga sedangkan pada bagian puncak berbentuk taring sesuai dengan keadaan Tugu saat ini. Perbedaan dalam penggambaran sosok Tugu dari kedua gambar tersebut mengindikasikan adanya makna filosofis yang berbeda. Meskipun di satu sisi penggambaran tugu dalam kedua logo ini sama-sama bertujuan untuk menunjukkan identitas sebagai Yogyakarta yang dikenal dengan Tugu-nya.

Beralih dari segi pemaknaan yang dilakukan oleh pemerintah pemaknaan mengenai Tugu juga menjadi berbeda dengan persepsi masyarakat lokal khususnya dikalangan keluarga Kraton, abdi dalem, budayawan, dan masyarakat yang masih memegang teguh nilai tradisi (Endraswara, 2006). Konstruksi filosofis dari Tugu Yogyakarta yang dibentuk menggunakan basis nilai-nilai budaya Jawa dan dianut oleh masyarakat menjadi penting untuk dipahami khususnya mengenai konteks di masyarakat. Pemaknaan secara kultural mengenai fungsi tugu sebagai penyambung antara Gunung Merapi, Kraton dan Pantai Selatan atau sumbu mistis sekiranya masih menjadi narasi utama dari berbagai booklet atau brosur pariwisata Yogyakarta.
Keselarasan Sejarah dan Pariwisata
Pengaruh penting sejarah dalam pembentukkan identitas atau ciri khas sebuah kota memiliki banyak implikasi pada kehidupan masyarakat kota modern. Kawasan perkotaan yang kini turut menjadi sebuah daerah pusat kegiatan modern menjadi sebuah fenomena menarim khususnya dalam rangka perubahan yang terjadi. Kota Yogyakarta yang kaya akan bangunan bersejarah, museum, dan monumen menjadi sebuah daya tarik tersendiri untuk berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan ini dilihat sebagai sebuah potensi wisata yang sangat menguntungkan jika dikelola dengan baik.
Pembangunan pariwisata di pusat kota yang sangat lekat dengan atraksi budaya dan sejarah telah melahirkan sebuah keuntungan secara finansial bagi kehidupan masyarakat dari sisi pariwisata. Narasi budaya dan sejarah sebagai daya dorong pengembangan wisata edukasi mendapatkan perlakuan khusus dalam pelaksanaannya. Museum dan monumen sebagai destinasi wisata memiliki peranan penting sebagai sarana membentuk pemahaman wisatawan mengenai sebuah lokasi. Konstruksi identitas sebuah wilayah dan keterkaitannya dengan berbagai sektor dalam lingkungannya menjadikan hal penting untuk dipahami pihak stakeholder untuk mengembangkan atau mempertahankan lajunya bisnis wisata edukasi ini (Zhang, et al., 2018).

Digunakannya narasi sejarah budaya dalam melakukan promosi pariwisata juga terjadi pada Tugu Yogyakarta. Monumen yang berada di pusat persimpangan antara Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Mangkubumi, dan Jalan AM Sangaji ini memiliki peranan penting dalam praktik wisata yakni sebagai ikon atau landmark. Fungsi dari kehadiran Tugu saat ini lenbih banyak dimaknai sebagai sebuah penanda bagi aktivitas wisata. Munculnya anggapan “belum ke Jogja kalo belum ke Malioboro dan foto di Tugu” seakan telah tertanam dalam benak wisatawan. Kawasan Tugu yang memang cukup ramai dilalui oleh berbagai aktivitas manusia sepanjang hari tidak menyurutkan minat wisatawan untuk berkunjung, mengamati, dan ber swafoto dengan latar belakang monumen ini. Pemahaman wisatawan akan keharusan untuk berfoto di Tugu sebagai bukti kunjungan mereka ke Yogyakarta telah tertanam subur dalam benak pegunjung dalam merencanakan liburan mereka.
Pada perkembangannya saat ini pemerintah daerah melakukan adanya pembangunan fasilitas penunjuang Tugu Yogyakarta sebagai destinasi wisata dengan membuat diorama mengenai sejarah dan makna filosofisnya. Diorama ini berada di sisi selatan Tugu Yogyakarta tepatnya di sebelah Pos Lantas di depan Jalan Mangkubumi. Pembangunan diorama ini adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota untuk memberikan sebuah pengalaman baru dalam memperoleh pengalaman wisata saat mengunjunginya. Tugu yang sarat makna dan kisah ini coba untuk diperlihatkan secara langsung kepada wisatawan melalui pembangunan diorama. Di dalam lokasi Diorama Tugu Yogyakarta ini dapat dengan mudah ditemukan informasi mengenai sejarah dan filosofi yang terkandung didalamnya. Adanya diorama ini seakan menegaskan Kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata sejarah budaya khususnya untuk Tugu. Kawasan sekitar Tugu yang ramai dikunjungi sebagai tempat foto semata oleh pemerintah mulai dicoba untuk dikembalikan makna pembangunannya melalui diorama. Pembangunan diorama ini terkesan lebih efektif untuk menjelaskan nilai dan makna yang terkandung dari Tugu sehingga edukasi dan kegiatan wisata dapat berjalan secara bersamaan.
Refleksi
Pembangunan Kota Yogyakarta yang semakin masif dilakukan dengan berdirinya fasilitas-fasilitas modern telah menandakan adanya perubahan dari sebuah kota. Perubahan sebuah kota yang sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi di masyarakat telah menyumbang konstruksi identitas dari sebuah kota (Hannerz, 1983). Dinamika sosial yang ditandai dengan makin beragamnya paham seseorang dalam memandang sesuatu telah menjadikan kota sebagai arena kontestasi paham dan kepentingan dimasyarakatnya. Pedoman pembangunan sebuah kota yang dipengaruhi oleh jejak historis dan nilai-nilai yang dianut masyarakatnya masih menjadi pokok utama dalam dilakukannya perencanaan pembangunan tidak terkecuali di Yogyakarta.
Kota Yogyakarta yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dalam menjalankan pembangunan dan perencanaan dengan berpedoman pada falsafah Jawa. Masifnya pembangunan fasilitas modern disekitaran kota bukan menjadi sebuah ancaman bagi komponen budaya yang usdah ada. Pengembangan dan eksplotrasi nilai dan citra Kota Yogyakarta sebagai daerah wisata budaya, dan sejarah tidak lepas dari adanya memori yang coba untuk dikisahkan kembali kepada masyarakat melalui bangunan dan monumen. Kolaborasi sektor pariwisata dengan memori kolektif yang ada dan dimaknai oleh sebagian masyarakat telah menjadi sumber ekonomi baru bagi pemerintah maupun masyarakat. Memori kolektif yang ditampakkan dari Tugu Yogyakarta menunjukkan peranan filosofi dan dinamika sosial pada tempo waktu tertentu telah membentuk konstruksi baru bagi masyarakat.
Berbagai narasi sejarah dan filosofis yang terus berkembang di kalangan wisatawan juga menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Perbedaan pemaknaan atas Tugu Yogyakarta sebagai sebuah bentuk memori kolektif dan destinasi wisata menjadi salah satu bentuk dari transformasi kota. Elemen fisik sebuah kota (bangunan, fasilitas publik, dan monumen) yang dikaitkan dengan nilai-nilai budaya dan filosofi yang ingin ditunjukkan masyarakat kepada pengunjung menjadi sebuah sarana untuk melihat bagaimana konstruksi identitas yang coba untuk dibentuk. Kota Yogyakarta dengan ekspresi budaya dan sejarah yang cukup kental terlihat diberbagai sudut kota ini telah menegaskan peran penting budaya dalam membentuk citra Yogyakarta sebagai sebuah kota budaya dan pariwisata.
Kolaborasi antara sejarah dan pariwisata telah memberikan sebuah hawa baru bagi masyarakat dan pengunjung untuk sama-sama membentuk identitas serta pemaknaan baru tentang Yogyakarta. Pemahaman sebagian masyarakat mengenai Tugu melalui narasi-narasi sejarah dan budaya yang terus menerus diceritakan kembali melalui buku, monumen, maupun lisan mulai disandingkan dengan kegiatan pariwisata. Wisatawan yang memaknai Tugu sebagai sebuah destinasi semata kini mulai dijejali dengan pengetahuan lokal masyarakat dan konteks pembangunannya untuk memberikan pemaknaan baru bagi mereka. Dengan diterimanya pengetahuan dan konteks lokal diharapkan akan terbentuk sebuah pemaknaan baru yang pada akhirnya akan membentuk sebuah memori kolektif baru sebagai turning point untuk melihat sejauh mana perubahan di kota terjadi bukan hanya aspek fisik namun juga aspek sosial.
Referensi
Buku dan Jurnal
Adi, S.W dan Edy P.S. 2017. “ Potensi Daya Tarik Wisata Sejarah Budaya “ dalam The 5th URECOL PROCEDDING (18 Feb) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
Ahimsa-Putra, H. S., 2001. "Remembering, Misremembering and Forgetting: The Struggle over": Serangan Oemoem 1 Maret 1949" in Yogyakarta, Indonesia". Asian Journal of Social Science, 29(3), pp. 471-94.
Endraswara, S., 2006. Falsafah Hidup Orang Jawa. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala.
Endraswara, S., 2015. Etnologi Jawa. Yogyakarta: CAPS.
Hannerz, U., 1983. Conclusion: The Construction of Cities and Urban Lives. In: U. Hannerz, ed. Exploring the City: Inquiries Towards an Urban Anthropology.. New York: Columbia University Press, pp. 242-315.
Haryono, A. Y., 2015. Penanda Kawasan Sebagai Penguat Nilai Filosofis Sumbu Utama Kota Yogyakarta. Atrium, 1(2), pp. 93-107.
Kusno, A. 2009. “Ruang Publik, Identitas, dan Memori Kolektif Pasca-Suharto”. Yogyakarta: Penerbit Ombak
Loughran, K., Fine, G. A. & Hunter, M. A., 2015. “Urban Spaces, City Cultures, and Collective Memories”. In: A. L. Tota & T. Hagen, eds. Routledge International Handbook of Memory Studies. New York: Routledge, pp. 193-204.
Morin, Lutse L Daniel. 2014. “Problematika Tugu Yogyakarta dari Aspek Fungsi dan Makna”. Journal of Urban Society’s Arts, 01(2), pp. 135-148.
Sumintarsih & Adriantro, A., 2014. Dinamika Kampung Kota Prawirotaman dalam Perspektif Sejarah dan Budaya. Cetakan pertama ed. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BNPB) Daerah Istimewa Yogyakarta.
Syakdiah. 2017. “Dinamika Pariwisata Daerah istimewa Yogyakarta” dalam ProsidingSeminar dan Call For Paper, 20-21 Oktober 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Wardani, L. K., 2008. The Power of Symbol at Keraton Yogyakarta. Cairo, The International Scientific Conference The Faculty of Fine Arts Centennial: Fine Arts in Egypt 100 Year of Creativity.
Zhang, C. X., Xiao, H., Morgan, N. & Ly, T. P., 2018. Politics of memories: Identity construction in museums. Annals of Tourism Research, Volume 73, pp. 116-130.
Sumber Internet
bernas.id, 2018. Aksi Solidaritas, Doa, dan Orasi Perdamaian Terkait Tragedi Surabaya di Tugu Jogja. [Online] Available at: https://www.bernas.id/63462-aksi-solidaritas-doa-dan-orasi-perdamaian-terkait-tragedi-surabaya-di-tugu-jogja.html [Accessed 23 June 2019].
Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2018. Tugu Yogyakarta bukan tugu sembarangan. [Online] Available at: https://pariwisata.jogjakota.go.id/detail/index/19 [Accessed 23 June 2019].
Heru, L., 2018. Tugu Manunggaling Kawula-Gusti. [Online] Available at: https://www.airmagz.com/19586/tugu-manunggaling-kawula-gusti.html [Accessed 23 June 2019].
Hipwee Community. 2016. Bikepacking Malang-Jogja-Semarang, Siapa Takut?. [Online] Available at: https://www.hipwee.com/list/bikepacking-malang-jogja-semarang-siapa-takut/ [Accessed 27 June 2019].
Humanitarian Response, 2012. Province Infographic: DI Yogyakarta. [Online] Available at: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/DI_YOGYAKARTA.pdf [Accessed 24 June 2019].
https://id.wikipedia.org/wiki/Tugu_Yogyakarta (Akses 22 Juni 2019, pukul 17:24)
https://id.wikipedia.org/wiki/ Kota_Yogyakarta (Akses 28 Juni 2019, pukul 07.55)
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta (Akses 28 Juni 2019, pukul 07.55)
Kompasiana. 2015. Mengawal City Branding Yogyakarta. [Online] Available at : https://www.kompasiana.com/wildanarrahman/%20552fa2e46ea8347c068b45df/mengawal-city%20branding%20yogyakarta [Accessed 26 June 2019].
Kraton Jogja, 2018. Tugu Golong Gilig, Simbol Persatuan Raja dan Rakyat. [Online] Available at: https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting-wewangunan/11/tugu-golong-gilig-simbol-persatuan-raja-dan-rakyat [Accessed 23 June 2019].
Kraton Jogja, 2019. Sri Sultan Hamengku Buwono I. [Online] Available at: https://www.kratonjogja.id/raja-raja/2/sri-sultan-hamengku-buwono-i [Accessed 23 June 2019].
Kurniawan, H., 2015. Ruang Publik Sejarah Kota. [Online] Available at: https://jogja.tribunnews.com/2015/10/08/diorama-tugu-ruang-publik-sejarah-kota-yogyakarta [Accessed 23 June 2019].
Love Heaven 07. 2016. Pesona Keindahan Tugu Jogja di Malam Hari. [Online] Available at: https://www.loveheaven07.com/2016/03/pesona-keindahan-tugu-jogja-di-malam-hari.html?m=1 [Accessed 27 June 2019].
http://pamungkaz.net/tugu-jogja-sejarah-dan-ikon-yogyakarta/ (Akses 22 Juni, pukul 20:18)
Pratama, Rony K. 2018. “Menggali Makna Filosofis Tugu-Keraton Yogya dalam Lipatan Imajiner”. Retrivied from :
Setyawan, E. D., 2019. Aksi “Kamisan” di Yogyakarta. [Online] Available at: https://muda.kompas.id/baca/2019/03/21/aksi-kamisan-di-yogyakarta/ [Accessed 23 June 2019].
Deni, 2015, “Taman Tugu Pal Putih, Kolaborasi Pemda DIY & Pemkot Jogja” [Online] Available at: https://www.starjogja.com/2015/10/06/taman-tugu-pal-putih-kolaborasi-pemda-diy-pemkot-jogja/ [Accessed 28 June 2019]
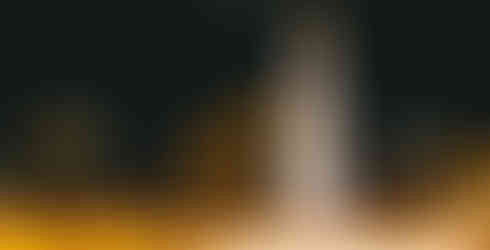





Comments